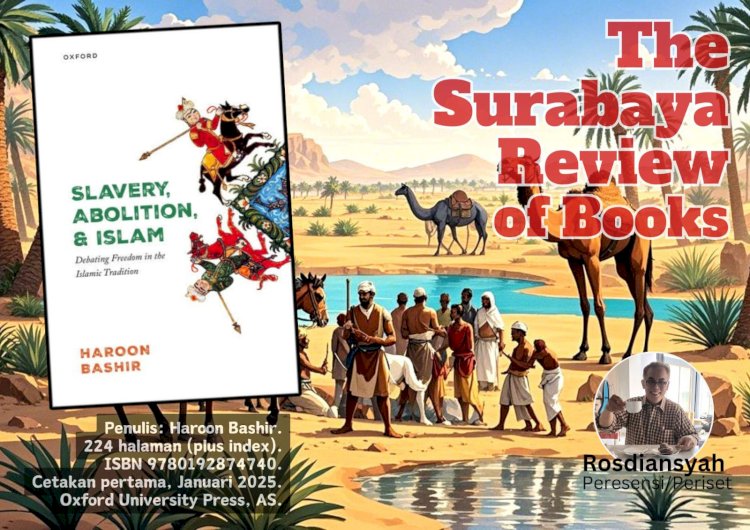- Metamorfosis Seni Persuasi Negeri Nipon
- Suku Hui, Patriot China Yang Terlupakan
- Kisah Islamofobia Yang Belum Usai
SAMPAI abad ke-19 praktek perbudakan dan selir masih menjadi fenomena yang lazim ditemui dalam masyarakat muslim. Fenomena ini tentu saja bertolak-belakang dengan praktek ajaran Islam yang telah dijalankan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di awal fajar Islam pada abad ketujuh.
Perbudakan sudah ada di dunia pra-Islam dan tidak dihapuskan secara eksplisit oleh kitab suci. Kitab suci mengakui kebolehan memiliki budak, tetapi juga memberikan peraturan untuk meringankan situasi mereka dan mendorong emansipasi terhadap mereka.
Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, terjadi pembatasan dalam perbudakan yang sah. Yakni, tawanan yang ditangkap dalam perang (bukan termasuk Muslim) atau lahir dalam perbudakan.
Selama berabad-abad, praktek perbudakan kembali marak di dunia Islam. Praktek ini dijalankan oleh sistem pemerintahan monarki yang sering mengadopsi tradisi lama perbudakan yang sudah lazim berlangsung di suatu wilayah. Ironinya, perdagangan budak juga lazim di wilayah mayoritas berpenduduk muslim.
Pada tahun 1871, pemikir India, Sayyid Ahmad Khan menulis risalah mengecam perdagangan budak yang saat itu marak di dunia Islam. Menurutnya, Islam tidak memperbolehkan perdagangan budak karena perbuatan itu adalah dosa. Ia mendesak pemerintahan manapun agar segera menghapus perdagangan budak tersebut. Baginya, menghubungkan ajaran Islam untuk membenarkan perbudakan dan perdagangan budak merupakan kesalahan penafsiran yang justru dipakai oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
Ditegaskan Khan, perbudakan dan perdagangan budak sangat jelas bertentangan dengan keadilan Ilahi. Tuhan tidak akan mendukung praktek-praktek perbudakan. Khan adalah satu diantara banyak intelektual muslim anti perbudakan pada abad ke-19.
Seruan Khan sarat etika emansipatoris pelanjut tradisi pembebasan dalam pemikiran Islam. Sembari merujuk ke Abu Hanifah, intelektual muslim abad ke-13, Al Qurtubi, menegaskan bahwa perbuatan membebaskan budak merupakan perbuatan mulia berpahala.
Fakta-fakta sejarah pembebasan budak di Afrika Utara, seperti di Timbuktu, menunjukkan perbuatan tersebut didorong motif emansipatoris. Bahkan kajian terhadap arsip-arsip dinasti Usmaniyah memperlihatkan juga motif tersebut walau seorang budak terlebih dulu berkewajiban mengabdi selama tujuh tahun sebelum bebas. Setelah tujuh tahun, otomatis dia bebas. Fakta ini sangat mengherankan orang-orang Eropa yang kemudian berkunjung ke wilayah tersebut. Sebab, di Eropa kala itu, budak bisa bebas hanya jika majikannya membebaskannya.
Ada kisah menarik dari khazanah sufisme. Adalah Rābi'a al-'Adawīyya yang ajaib (wafat 801), dia berubah dari gadis yatim piatu yang diperbudak menjadi status suci Sufi yang terhormat. Alkisah, kemampuan Rābi'a untuk menyulap cahaya dari ujung jarinya, menghasilkan koin emas, dan bakatnya untuk berdoa dengan untaian kalimat begitu indah lantas membuat tuannya memberinya kebebasan. Kisah ini menunjukkan betapa seorang budak pun mempunyai ruang untuk berekspresi, status budak tak menghalanginya untuk menunjukkan keterampilan atau kemahirannya yang sangat luar biasa.
Penulis buku ini kemudian bertanya, mengapa para intelektual Muslim tidak secara aktif melarang perbudakan dan selir sampai abad kesembilan belas? Ini tetap menjadi titik kontestasi utama bagi para cendekiawan Muslim yang mendukung penghapusan. Jika diterima bahwa Islam mendorong penghapusan perbudakan, mengapa Muslim dan tradisi Islam justru malah mengatur dan mengizinkan perbudakan selama ratusan tahun? Dari beragam pertanyaan ini kemudian penulis melacak perdebatan bertopik penghapusan perbudakan di kalangan intelektual muslim.
Perdebatan tersebut mengarah pada perkembangan 'abolisionisme Islam', sebuah wacana ilmiah berpengaruh yang berpendapat bahwa Islam menentang perbudakan. Formasi interpretatif ini mengembangkan hermeneutika penuh pada abad ke-19, dan abolisionis Islam menggunakan argumen dan metode yang berbeda dalam upaya mereka untuk mempertemukan cita-cita penghapusan perbudakan dengan tradisi agama Islam.
Pada masa Islam klasik, para cendekiawan Muslim menerima legitimasi perbudakan dan mengatur praktik tersebut. Perbudakan dianggap sebagai bagian dari ujian ilahi, baik untuk tuan maupun budak, yang dicontohkan oleh pernyataan ''Tuhan telah menghormati beberapa dari kamu di atas orang lain''.
Emansipasi untuk pembebasan selalu dianggap sebagai tindakan mulia dan berpahala, meski pada masa itu perbudakan sebagai institusi tidak dianggap bermasalah. Kehadiran para intelektual reformis muslim pada abad ke-19 kian mempertegas wacana serta sikap 'abolisionisme Islam' bertumpu dari etika emansipatoris. Para reformis ini berkeyakinan, bahwa penghapusan perbudakan sejalan dengan pandangan dunia Islam.
Akhirulkalam, buku ini bisa melengkapi sekaligus menjelaskan lebih mendalam bagaimana etika emansipatoris dalam ajaran Islam sesungguhnya mendukung Konvesi PBB tentang penghapusan perbudakan dan perdagangan budak yang dirilis tahun 1956. Sejak konvesni ini dirilis memang kemudian memantik perdebatan seru tentang 'abolisionisme Islam' itu. Setidaknya, buku ini memberi semacam peta pemikiran (mindmapping) para intelektual muslim yang menjadi rujukan masyarakat awam yang mendukung penghapusan perbudakan.
Penulis adalah akademisi dan periset
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Metamorfosis Seni Persuasi Negeri Nipon
- Suku Hui, Patriot China Yang Terlupakan
- Kisah Islamofobia Yang Belum Usai